 Kuntoro Boga
Kuntoro Boga
Indonesia di Persimpangan Krisis Iklim dan Keemasan Komoditas
Bisnis | 2025-02-02 11:45:13Pada tahun 2024, Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) melaporkan bahwa suhu global mencapai rekor tertinggi, dengan rata-rata 1,55°C di atas tingkat pra-industri. Kondisi ini menyebabkan kekeringan parah di Afrika Barat dan banjir bandang di Asia Tenggara. Akibatnya, produksi kakao global menurun signifikan, dengan penurunan sebesar 18% yang menciptakan defisit sekitar 600.000 ton—angka tertinggi sejak 1990. Ghana dan Pantai Gading, yang menyumbang 70% produksi kakao dunia, mengalami gagal panen akibat kondisi cuaca ekstrem dan penyakit tanaman. Sebaliknya, Indonesia mencatat peningkatan ekspor kakao sebesar 5,8% pada periode Januari hingga November 2024, meskipun dari basis produksi yang relatif kecil.
Di komoditas kopi, negara-negara produsen utama seperti Brasil dan Vietnam mengalami penurunan produksi akibat kondisi cuaca ekstrem dan serangan hama. Permintaan kopi global meningkat sebesar 7%, didorong oleh pertumbuhan budaya kafe di China dan Timur Tengah. Kopi asal Sumatera dan Jawa menjadi incaran pasar premium di Eropa, dengan harga biji kopi Gayo Arabica mencapai USD 8 per kilogram, meningkat 25% dalam setahun.
Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun perubahan iklim membawa tantangan besar bagi produksi komoditas perkebunan global, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan perannya di pasar internasional. Namun, untuk memanfaatkan peluang ini secara optimal, diperlukan strategi yang tepat dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas produk, serta adaptasi terhadap perubahan iklim yang semakin tidak menentu.

Kondisi yang Membuka Peluang
Kelapa sawit tetap menjadi komoditas andalan Indonesia yang sarat kepentingan bisnis dan kontroversi bagi pihak lain. Pemerintah berencana menerapkan mandatori biodiesel B40—campuran 40% biodiesel berbasis minyak sawit dengan 60% solar—mulai 1 Januari 2025, dengan alokasi sebesar 15,6 juta kiloliter per tahun. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkan permintaan domestik minyak sawit.
Namun, kebijakan ini mendapat tantangan dari Uni Eropa yang memperketat regulasi rantai pasok bebas deforestasi, mengingat kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dari ekspansi perkebunan sawit. Ironisnya, peningkatan harga minyak sawit mentah (CPO) yang mencapai USD 877,28 per metrik ton pada Mei 2024 justru dipicu oleh tantangan produsen dalam memenuhi permintaan pasar yang terpecah antara kebutuhan energi hijau dan tekanan lingkungan.
Di tengah dinamika ini, Indonesia memiliki potensi besar dengan adanya sekitar 14 juta hektar lahan terdegradasi yang dapat direhabilitasi untuk perkebunan berkelanjutan. Inisiatif seperti Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan penerapan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) versi terbaru pada tahun 2024 dapat menjadi solusi atas kritik global, asalkan diimplementasikan dengan transparan dan efektif.
Sementara perhatian dunia tertuju pada komoditas seperti kelapa sawit dan kakao, vanili dan lada Indonesia menawarkan potensi yang signifikan. Harga vanili kering di Indonesia berkisar antara Rp4 juta hingga Rp6 juta per kilogram, didorong oleh permintaan dari industri parfum Prancis dan makanan gourmet di Amerika Serikat. Namun, banyak petani masih mengandalkan metode budidaya tradisional yang rentan terhadap perubahan iklim.
Di sisi lain, Vietnam, sebagai produsen lada terbesar dunia, baru-baru ini mengalami penurunan produksi sekitar 30% akibat serangan penyakit layu cepat. Hal ini membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor lada hitam ke pasar Eropa, terutama dengan keunggulan lada Muntok yang telah memiliki indikasi geografis. Dengan memanfaatkan peluang ini melalui peningkatan kualitas dan produktivitas, Indonesia dapat memperkuat posisinya di pasar global untuk komoditas vanili dan lada.
Strategi dan Agenda Darurat
Selain revolusi teknologi, Indonesia harus memperkuat diplomasi perdagangan hijau untuk memastikan produk pertaniannya tetap kompetitif di pasar global. Uni Eropa telah menerapkan pajak karbon pada produk pertanian (carbon border tax), yang berpotensi menjadi hambatan bagi ekspor Indonesia. Untuk mengatasi ini, Indonesia perlu memperkuat strategi diplomasi berbasis sertifikasi hijau agar komoditasnya tetap diterima di pasar Eropa. Salah satu langkah konkret yang bisa diambil adalah memperluas kolaborasi dengan negara-negara yang telah menerapkan standar keberlanjutan, seperti proyek kopi karbon-netral di Toraja yang bekerja sama dengan Jerman. Model ini dapat dijadikan contoh bagaimana Indonesia dapat menyesuaikan diri dengan regulasi global sambil tetap mempertahankan daya saing produknya.
Di sisi lain, diversifikasi pasar dan hilirisasi industri perkebunan harus menjadi prioritas utama. Ketergantungan pada pasar tradisional seperti China dalam ekspor sawit merupakan risiko besar bagi stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih agresif dalam membuka pasar baru, terutama di kawasan Afrika Sub-Sahara dan Timur Tengah yang memiliki permintaan tinggi terhadap produk perkebunan. Selain itu, hilirisasi juga harus segera dipercepat agar Indonesia tidak hanya menjadi eksportir bahan mentah, tetapi juga produsen produk bernilai tambah tinggi. Sebagai contoh, ekspor biji kakao dapat ditingkatkan menjadi produk cokelat premium seperti "Java Gold," yang memiliki nilai jual hingga lima kali lipat lebih tinggi dibandingkan biji kakao mentah. Dengan menerapkan strategi hilirisasi yang tepat, Indonesia dapat mengoptimalkan keuntungan dari komoditas perkebunannya dan memperkuat daya saing di pasar global.
Tiga agenda ini—revolusi produktivitas berbasis teknologi, diplomasi perdagangan hijau, dan diversifikasi pasar serta hilirisasi—harus segera diterapkan agar Indonesia tidak hanya bertahan di tengah dinamika pasar global, tetapi juga menjadi pemimpin dalam industri perkebunan dunia. Tanpa langkah strategis yang konkret, Indonesia berisiko kehilangan momentum dan tertinggal dalam persaingan global.
Saatnya Menetukan Kesuksesan
Presiden Jokowi, dalam KTT G20 2024, menegaskan bahwa Indonesia harus menjadi laboratorium agroteknologi tropis dunia. Untuk mewujudkan visi ini, diperlukan percepatan adopsi teknologi pertanian presisi, seperti penggunaan sensor IoT untuk memantau kelembapan tanah dan drone untuk penyemprotan pestisida. Contoh sukses telah terlihat di Sulawesi, di mana perkebunan kakao yang menerapkan kecerdasan buatan untuk memprediksi waktu panen berhasil meningkatkan produktivitas dari 0,5 ton per hektar menjadi 1,2 ton per hektar dalam dua tahun.
Selain itu, Uni Eropa kini menerapkan pajak karbon pada produk pertanian. Untuk menghindari diskriminasi, Indonesia perlu memperkuat diplomasi berbasis sertifikasi hijau. Kolaborasi dengan Jerman dalam proyek kopi karbon-netral di Toraja dapat menjadi model yang patut ditiru.
Ketergantungan pada pasar tradisional, seperti Tiongkok untuk ekspor kelapa sawit, ibarat bom waktu. Pemerintah harus agresif membuka pasar baru di Afrika Sub-Sahara dan Timur Tengah. Hilirisasi juga wajib dipercepat; misalnya, daripada hanya mengekspor biji kakao, Indonesia bisa memproduksi cokelat batang premium seperti "Java Gold" yang memiliki nilai jual lima kali lipat lebih tinggi.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.




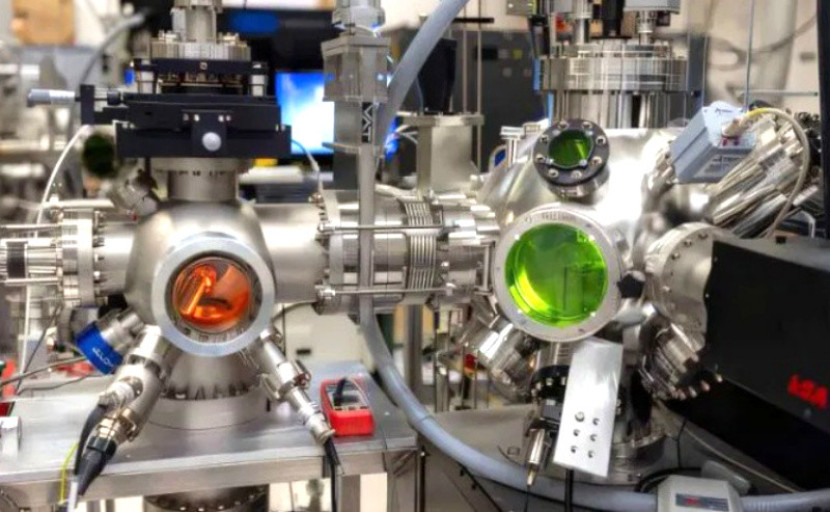



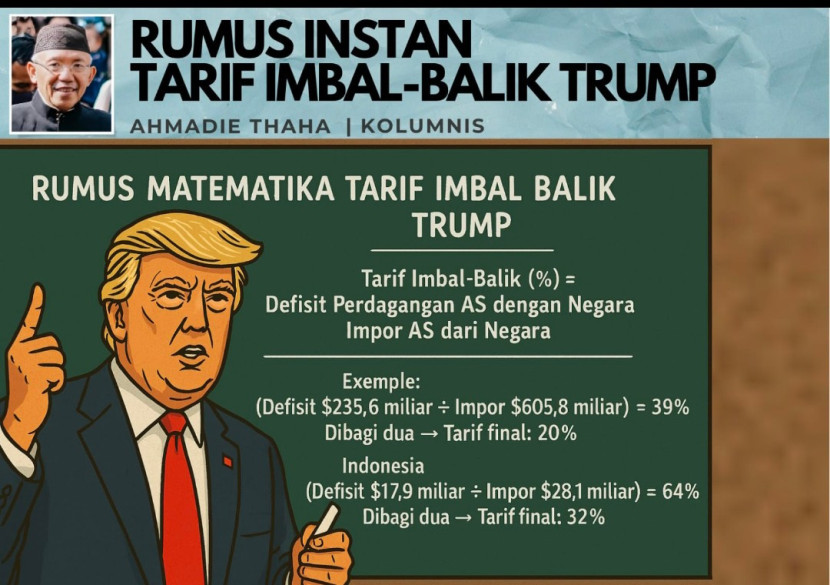

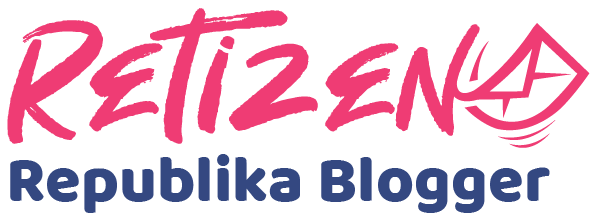
Komentar
Gunakan Google Gunakan Facebook